THEREPUBLIKA.ID, HONG KONG- Hong Kong kembali berduka. Kebakaran hebat yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di kawasan New Territories menewaskan 151 orang, menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah modern kota itu. Namun, di balik kepulan asap dan duka yang menyelimuti warga, muncul kekhawatiran lain yang tak kalah besar: menyusutnya perbedaan antara Hong Kong dan China daratan dalam hal kebebasan sipil, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Pemimpin Hong Kong John Lee, Selasa, 2 Desember 2025 mengumumkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Model penyelidikan semacam itu merupakan tradisi lama Hong Kong, warisan dari sistem hukum yang diwariskan Inggris.
Namun, para pakar hukum menilai ruang independensi itu terus menipis sejak berlakunya dua Undang-Undang Keamanan Nasional pascaprotes prodemokrasi 2019–2020. Mantan hakim Mahkamah Agung Inggris, Jonathan Sumption, bahkan mundur dari Pengadilan Banding Hong Kong dengan menyebut bahwa “supremasi hukum dapat dikompromikan jika pemerintah menghendakinya.”
Kebakaran fatal tersebut terjadi setelah warga berbulan-bulan mengeluhkan penggunaan material konstruksi yang mudah terbakar. Polisi telah menangkap 13 orang, sebagian merupakan pekerja perusahaan konstruksi. Hingga kini, belum ada pejabat pemerintah yang dimintai pertanggungjawaban.
Tragedi ini diperkirakan akan memengaruhi pemilihan legislatif (LegCo) akhir pekan ini. Namun, pemilu tersebut berlangsung dalam format baru: hanya kandidat “patriot” yang mendapat persetujuan pemerintah dapat ikut serta. Hampir seluruh tokoh oposisi telah dipenjara, dibungkam, atau memilih meninggalkan Hong Kong.
Pada pemilu 2021 pemilu pertama dengan aturan “patriots only” partisipasi pemilih merosot ke angka 30,2 persen, terendah dalam sejarah Hong Kong. Boikot menjadi satu-satunya bentuk penolakan yang tersisa, di tengah kriminalisasi hampir seluruh bentuk protes.
Akhir pekan lalu, seorang mahasiswa, Miles Kwan, ditangkap setelah menginisiasi petisi yang menyoroti kurangnya akuntabilitas pemerintah atas bencana ini. Media lokal melaporkan dua penangkapan lain terkait aksi serupa.
Perbedaan antara Hong Kong dan China daratan masih tampak, meskipun makin mengecil. Di Hong Kong, kritik terbatas masih dapat dilontarkan. Dalam sebuah konferensi pers, seorang jurnalis AFP bahkan bertanya langsung kepada John Lee:
“Anda berjanji membawa Hong Kong dari kekacauan menuju kemakmuran. Namun 151 orang meninggal dalam kebakaran di kota yang Anda pimpin. Mengapa Anda layak mempertahankan jabatan Anda?”
Pertanyaan seperti itu nyaris mustahil diajukan secara publik kepada Presiden Xi Jinping di Beijing.
Selain itu, meskipun kebebasan pers di Hong Kong telah jauh menyusut, kota ini masih memiliki ruang informasi yang lebih terbuka dibanding China daratan. Platform seperti Google dan media sosial barat tetap bisa diakses. Sebaliknya, di China daratan, sebuah artikel yang mengkritik risiko pembangunan ala Hong Kong langsung dihapus dari internet.
Tragedi Wang Fuk Court juga memunculkan kembali ingatan publik pada kebakaran apartemen di Urumqi, Xinjiang, pada 2022. Kebakaran yang menewaskan sembilan orang itu memicu demonstrasi besar terhadap kebijakan nol-Covid, kemudian berkembang menjadi Gerakan Kertas Putih protes terbesar terhadap pemerintah China sejak 1989.
Di China daratan, negara berupaya menghapus memori tentang tragedi Urumqi dan protes Tiananmen. Namun, di Hong Kong, meski tekanan politik terus meningkat, ingatan publik sulit dipadamkan.
Tragedi ini bukan hanya persoalan keselamatan publik. Wang Fuk Court menjadi ujian besar bagi Hong Kong untuk menunjukkan apakah tradisi transparansi, kebebasan sipil, dan integritas sistem hukumnya masih dapat dipertahankan di tengah tekanan politik dari Beijing.
Bagi banyak warga, api yang membakar gedung itu seolah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: memudarnya identitas Hong Kong sebagai kota yang berbeda dari China daratan.









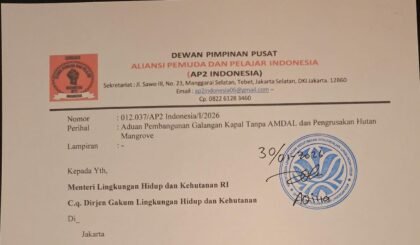










Komentar